BAB 1
“Nim, kau kena tolong aku lagi, Nim…” ujar Iqbal resah.
Hanim menjeling rakan sekelasnya itu dengan jelingan yang tajam.
“Aku tak tahu apa lagi yang kau tak puas hati dengan si
Laila tu! Aku rasa dia dah cukup baik untuk lelaki macam kau, tapi kau selamba
je lukakan hati dia. Dia bagai nak mati sayang kat kau, tapi kau sedap-sedap je
tuduh dia bukan-bukan. Mhm…!” dengus Hanim bengang. Terbayang di matanya
bagaimana sedihnya Laila, rakan sebiliknya itu apabila dituduh berlaku curang.
“Aku terlampau marah masa tu. Dia langsung tak bagitahu itu
abang dia. Kalau kau tengok kemesraan diorang hari tu, kau mesti takkan fikir
itu abang dia. Mesra sangat!” kata Iqbal lagi. Hanim yang bertubuh agak besar
itu bangun dari kerusi taman rekreasi itu dengan keluh berat.
“Aku tak tahu nak kata apa lagi kat kau ni. Cuba kau ingat
balik, semester ni je dah tiga kali kau lukakan dia dan tiga kali jugaklah kau
cari aku untuk pujuk dia. Kau ingat aku dah takde kerja lain ke? Takkan kau tak
tahu yang Laila tu anak perempuan tunggal? Dia tak cerita ke pasal adik-beradik
dia kat kau?” soal Hanim tegas. Muka kacak di hadapannya ditenung tajam.
“Ada, tapi aku tak suspect itu abang sulung dia. Mamat tu
macho sangat, tergugat aku!” Iqbal meraut muka resah. Hanim ketawa sinis.
“Kau ni harap muka je handsome, tapi keyakinan kau zero!”
kutuk Hanim dengan tawa bersisa. Jam ditangannya dijeling sekilas.
“Iqbal, dah petang ni. Aku nak balik dulu. Dahlah kau suruh
aku turun bandar ni. Entah pukul berapa pulaklah aku sampai rumah nanti. Pasal
Laila tu bagi aku masa sikit. Bukan senang nak pujuk minah tu. Kau pun kena
usaha sendiri dan ini last aku tolong kau. Lepas ni, jangan harap!” ujar Hanim
selamba. Beg sandangnya disangkut ke bahu. Iqbal tersenyum gembira.
“Thanks, Hanim! Kau lah sahabat aku dunia akhirat. Aku
takkan lupa semua jasa baik kau. Thanks!” ulang Iqbal lagi. Hanim mengangkat
kening lalu mereka pun berpecah menuju haluan masing-masing.
Setibanya Hanim di sebuah bangunan sepuluh tingkat, dia
terus menaiki lif menuju ke tingkat 7. Keluar sahaja dari lif, Hanim terus
menuju ke sebuah apartment yang terletak di hujung tingkat itu. Segugus kunci
dalam beg sandangnya dikeluarkan lalu dicucuh ke dalam tombol pintu. Tidak
sampai seminit, pintu itu sudah dapat dibuka. Sebaik sahaja Hanim melangkah
masuk, matanya tertancap pada sesusuk tubuh yang sedang termenung di beranda
yang menghadap terus ke laut Selat Melaka itu. Kepalanya digeleng perlahan. Beg
sandangnya diletak di atas sofa lalu merapati tubuh berambut lurus separas bahu
itu.
“Assalamualaikum?” tegur Hanim mesra. Bahu rakan
sebiliknya, Laila dipeluk erat. Laila mengesat airmata dan menjawab salam.
“Dahlah tu, Ila. Aku risau tengok kau macam ni. Iqbal tak
bermaksud nak lukakan hati kau. Ini hanya satu salah sangka je…” ujar Hanim
memujuk.
“Dia jumpa kau lagi?” soal Laila dengan mata terus
menikmati keindahan alam di hadapannya.
“Ha’ah. Aku sebenarnya dah taknak campur hal korang lagi.
Tapi aku pun tak tergamak nak tengok kawan aku macam ni. Dahlah tu, maafkan
dia,” sambung Hanim lagi.
“Bukan aku taknak maafkan dia, Nim. Tapi dia tu suka tuduh
aku macam tu. Siapa tak sedih kalau kita punya setia dengan orang tu, tapi
orang tu tak nampak kesetiaan kita. Semua sedih, Nim…” luah Laila sayu.
“Aku faham. Aku jugak tahu yang kau terlalu sayangkan dia.
Dia pun sayangkan kau, Laila. Dia cemburu sebab dia tergugat tengok abang kau
macho sangat!”
“Dia cakap macam tu?” soal Laila terkejut. Hanim mengangguk
dengan senyuman.
“Merepek je dia tu!” rungut Laila. Hanim ketawa lucu
melihat sekuntum senyum terukir di bibir Laila.
“Ha, macam tulah! Kau kalau senyum, nelayan tu pun boleh
karam tau!” usik Hanim nakal.
“Macam tu sekali?”
“Yelah, bila kau senyum, laut pun boleh berdebar tau!” usik
Hanim lagi.
“Ada-ada je kau ni!” Hanim ketawa.
“Okeylah, malam nanti Iqbal telefon, kau jangan nak jual
mahal pulak. Aku nak masuk mandi dulu! Jangan lama-lama sangat kat luar ni, dah
nak senja tu!” pesan Hanim lalu masuk ke dalam biliknya yang terletak tidak
jauh dari beranda tadi.
BAB 2
Hanim keluar dari bilik setelah selesai solat Isyak.
Kelihatan Laila sedang asyik berbual di telefon bimbitnya di beranda. Manakala
dua orang rakan serumahnya lagi sedang menonton televisyen bersama-sama. Hanim
lantas menyertai dua orang gadis itu iaitu Zulaikha dan Irni.
“Pukul berapa korang balik tadi? Kalau tak salah aku, kelas
korang habis awal tadi kan?” tanya Hanim sekadar mengambil tahu.
“Aku teman si Irni ni beli buku kat bandar. Kau tahu jelah,
Irni kalau dah dapat ke bandar, mana ingat nak balik?!” jelas Zulaikha selamba.
Irni mencebik tanda tidak ambil tahu.
“Eh, korang tak lapar ke? Aku rasa nak makan kat luar lah
malam ni,” ujar Hanim tiba-tiba.
“Kitorang dah makan tadi. Tapi tadi aku dengar Ila kata nak
keluar makan dengan Iqbal. Kau join lah diorang sekali. Kau kan memang suka
teman diorang dating…?” celah Irni pula. Hanim merenung Laila yang sedang
menutup pintu beranda.
“Ha’ah, Hanim. Iqbal pun suruh aku ajak kau sekali. Dia nak
belanja makan!”
“Belanja? Ha, tu yang aku nak dengar tu!” Hanim pantas
bergegas ke bilik bersama Laila.
“Untung si Hanim tu kan, Ika? Dia teman orang dating, tak
payah keluar duit pun! Tak macam aku ni, teman kawan dating kena keluar duit
sendiri,” keluh Irni dengan nada seperti kecil hati. Zulaikha menjeling tajam.
“Kau tak payahlah perli aku. Kau kena faham, Arman dan
Iqbal tu berbeza. Iqbal duduk dengan keluarga. Arman tu pulak hidup macam kita
ni yang ada duit lebih sikit, baru dapat rasa makan kat kedai. Kalau tak,
menangis potong bawang je la…” balas Zulaikha selamba. Seketika kemudian, Hanim
dan Laila keluar dari bilik siap bertudung dan memakai baju lengan panjang.
“Ha, korang nak pesan apa-apa tak?” tanya Laila sebelum
mengekori Hanim yang sudah keluar dari apartment itu.
“Oleh kerana pakwe kau bermurah hati malam ni, aku nak
pesan beli nasi goreng ayam satu,” pesan Zulaikha selamba.
“Same to me!” celah Irni pantas. Laila mengangguk lalu
menutup pintu apartment yang sudah hampir dua tahun dikongsi bersama rakan
sekolejnya itu.
Hanim dan Laila turun ke bawah dan menuju ke pondok bas yang
terletak tidak jauh dari apartment itu. Lima minit kemudian, Iqbal dan Husyairi
kawan rapatnya tiba dengan motor masing-masing.
“La, apasal kau naik motor Iqbal? Ni yang lemah ni!” rungut
Hanim. Laila sudah pun membonceng motor kekasihnya. Husyairi tersengih dengan
rungutan Laila.
“Hus, kau boleh ke bonceng aku ni?” soal Hanim bimbang. Dia
masih ingat pengalaman pahitnya membonceng motor bersama seorang rakannya yang
turut dibesarkan di rumah anak yatim sepertinya. Rakannya itu tidak dapat
mengimbangi motor yang mereka naiki dan akhirnya merempuh sebatang pokok
kelapa.
“Naiklah, saya boleh la…” jawab Husyairi tenang dengan
senyuman. Husyairi jarang bertemu dengan Hanim kerana dia belajar di kolej yang
berlainan. Perkenalan mereka bermula ketika menemani Iqbal dan Laila berjumpa
buat pertama kali kira-kira setahun yang lalu. Tapi Husyairi baru tiga kali
menemani pasangan itu sepanjang tempoh tersebut.
“Kau jangan bawak laju-laju. Aku takut!” saran Hanim
awal-awal. Husyairi ketawa mendengar kata-kata itu. Hanim berhati-hati
membonceng motor Kriss itu.
“Kalau awak takut, pegang bahu saya atau peluk je pinggang saya,”
pesan Husyairi sebelum bergerak mengejar Iqbal yang sudah jauh di hadapan.
Hanim memegang bahu Husyairi sekuat yang mungkin.
Mereka berhenti di sebuah restoran makanan laut yang dibuka
24 jam. Hanim segera turun sebaik sahaja Husyairi memberhentikan motornya.
“Fuh, menggigil kaki aku! Dahsyat jugak kau ni bawak
motor!” komen Hanim sambil mengurut lututnya yang menggeletar. Laila dan Iqbal
ketawa. Husyairi hanya tersenyum.
“Awak tak pernah naik motor ke?” tanya Husyairi sambil
membukakan helmet di kepala Hanim. Hanim menggeleng.
“Patutlah…” ujar Husyairi tenang. Mereka berempat masuk ke
restoran itu dan duduk di sebuah meja empat segi tepat. Laila duduk menghadap
Iqbal begitu juga dengan Hanim.
“Ramai jugak budak kolej kita kat sini kan? Tapi tak nampak
pun budak kos aku?” soal Hanim sambil memandang sekeliling.
“Kau tu ambil rekaan grafik. Sepatutnya, budak grafik macam
kau ni, melukis cari ilham kat rumah. Bukan lepak kat luar malam-malam ni…”
ujar Iqbal selamba.
“Ya tak ya jugak. Eh, tapi tak semua budak grafik macam tu.
Contohnya, aku. Aku kena keluar cari ilham. Barulah lukisan aku tu nampak
semulajadi!” kata Hanim penuh semangat.
“Kau kalau sebut pasal lukisan, hidup je!” perli Laila
selamba. Husyairi tersengih melihat kesungguhan gadis gempal di hadapannya.
“Awak berdua nak tahu, kat dalam bilik tidur kami, penuh
dengan lukisan je! Lukisan burung lah, lautlah, air terjun lah. Gambar kita
berdua pun dia lukis tau!” cerita Laila sambil menjeling Hanim sekilas.
“Really?” soal Iqbal kagum.
“Bukan tu aje. Aku sekarang tengah siapkan gambar anak yang
bakal korang lahirkan nanti. Nanti dah siap, aku bagi tapi korang kena janji
dengan aku, jangan gaduh-gaduh lagi, tau?!” pesan Hanim tegas. Iqbal dan Laila
tersengih. Husyairi hanya diam tersenyum. Ketika itu juga seorang pelayan
datang mengambil pesanan. Malam itu, mereka memesan makanan ala-ala BBQ seperti
ikan bakar, sotong dan udang bakar dan banyak lagi.
Ketika sedang leka makan, Hanim terpandang ke satu wajah
yang amat diminatinya. Laila dan Iqbal sedang leka berbual. Hanya Husyairi yang
perasan perubahan Hanim yang sedang merenung sesuatu dengan senyum meleret
seolah-olah sedang berkhayal. Husyairi memandang ke arah pandangan Hanim.
Kelihatan sepasang kekasih yang sama cantik dan sama padan.
“Handsomenya dia…” keluh Hanim masih tidak lepas-lepas dari
merenung raut wajah itu. Laila dan Iqbal berhenti berbual lalu memerhatikan
Hanim begitu juga dengan Husyairi.
“Hanim, kau ni tak habis-habis minat kat si Shah tu! Tahu
dek Nadia tu nanti, azab kau!” tegur Laila tegas. Dia tahu Hanim meminati
pemuda kacukan itu sejak dari semester pertama lagi.
“Ala, aku pandang je. Tak luak pun!” ujar Hanim selamba
lalu menyambung makannya. Laila merenung Hanim. Dia tahu Hanim meminati Shahril
dalam diam. Kerana minat itu juga, Hanim sentiasa mengikuti perkembangan jejaka
idaman itu.
“Hanim, aku rasa, baik kau terus terang je dengan Shah tu
yang kau minat kat dia. Kalau kau malu, aku boleh tolong. Lagipun, dia satu
makmal dengan aku!” ujar Iqbal pula.
“Hish, jangan kau! Aku taknak dia tahu aku minat kat dia.
Nanti dia fikir aku ni tak tahu malu pulak!” bantah Hanim pantas. Iqbal dan
Laila mengangkat bahu.
“Kenapa awak suka dengan dia?” tanya Husyairi tiba-tiba
setelah sekian lama membisu.
“Sebab dia handsome, bijak dan paling best, ramai yang
cakap dia baik. Suka tolong kawan-kawan yang dalam kesusahan…” jawab Hanim
dengan senyuman.
“Jangan terlalu dengar kata orang. Selalunya, khabar angin
tu hanya sekadar indah khabar dari rupa. Kat kolej saya ramai lelaki macam tu.
Jangan terpedaya dahlah,” ujar Husyairi lagi. Dia lebih gemar menggunakan
gelaran saya dan awak walaupun Hanim hanya ber ‘aku kau’.
“Tapi, aku tak rasa semua lelaki macam Shah tu, macam tu.
Shah tu nampak je macam playboy. Tapi aku yakin, dia sebenarnya baik,” kata
Hanim penuh yakin. Husyairi hanya tersengih.
“Hus, awak jangan kutuk Shah depan Hanim ni. Awak cakaplah
Shah tu macam pisau cukur pun, dia tetap anggap Shah tu macam dewa!” celah
Laila. Husyairi tersengih.
“Takde la sampai tahap dewa. Iman kat dada aku ni mantap
lagi, Laila…” balas Hanim selamba.
“Hus, macamana hubungan kau dengan Maria?” tanya Iqbal
sekadar mengalih topik perbualan.
“Kami okey. Buat masa ni takde masalah,” jawab Husyairi
endah tidak endah. Dia seperti tidak berminat untuk berbicara tentang kekasih
yang sudah bertahun disayanginya itu. Hanim merenung Husyairi sebentar dan
kemudian tersenyum sendiri.
Mamat ni sekali
aku tengok handsome jugak! Dahlah Hus. Tengok muka pun aku tahu kau tu jawab
tak ikhlas! Eleh…
“Apa yang awak senyum?” soal Husyairi perlahan. Laila dan
Iqbal pergi membayar makanan yang dimakan.
“Salah ke saya senyum? Sekurang-kurangnya, senyuman saya
sekarang ni lebih ikhlas dari jawapan awak pada Iqbal tadi…” jawab Hanim
selamba tanpa menyedari dia sudah menukar panggilannya. Husyairi tersengih.
“Akhirnya awak ber ‘saya awak’ jugak dengan saya kan?” usik
Husyairi dengan senyuman. Hanim tersentak.
“Eh, aku cakap saya awak ke tadi?” soal Hanim seperti orang
bingung.
“Takkan awak tak sedar apa yang awak cakap? Takpelah. Sedap
sikit telinga saya ni dengar. Aku kau tu terlalu kasar pulak bagi saya. Tapi
itu tak bermakna saya marah awak bergelar begitu.”
“Aku kadang-kadang, kalau tengah berbual dengan orang macam
kau ni, tersasul jugak. Sorry ye…” Hanim tersengih nakal. Husyairi ketawa kecil
melihat senyum nakal itu. Iqbal dan Laila menghampiri mereka.
“Lepas ni nak pergi mana? Baru pukul 9. Kitorang takde
kelas pagi esok. Kau macamana Hus, Nim?” tanya Iqbal yang sekelas dengan buah
hatinya.
“Aku kelas petang esok…” jelas Husyairi. Sekarang, semua
mata merenung Hanim yang senyap.
“Aku? Err… aku ada kelas pagi tapi pukul 10. So, aku rasa
aku okey…” jawab Hanim selamba.
“Iqbal, awak tak payah tanya Hanim ni. Dia ni, kalau kat
rumah tu, pukul 2 pagi pun boleh nampak dia depan kertas kanvas dia!” sampuk
Laila dengan nada menyindir.
“Ha, tu yang korang tak tahu! Pagi-pagi macam tu la ilham
aku datang. Kalau nak baca buku pun, rasa best je!” ujar Hanim selamba. Mereka
berempat beredar menuju ke motor mereka.
“Okey, kalau semua takde masalah, kita pergi jalan-jalan
kat tepi pantai. Amacam?” cadang Iqbal. Semua tersengih dan mengangguk. Mereka
membonceng motor masing-masing dan menuju ke sebuah pantai yang agak lengang.
Iqbal dan Laila membawa haluan mereka manakala Hanim dan Husyairi hanya duduk
tidak jauh dari tempat motor mereka diletakkan.
“Hus, dah lama ke kau kenal dengan Iqbal tu?” soal Hanim
memulakan perbualan setelah hampir sepuluh minit kesunyian mengelilingi mereka.
“Iqbal? Lama jugak. Sejak dari tingkatan satu. Masa tu,
Iqbal dan family dia pindah ke sebelah rumah saya. Sekolah pulak satu kelas,
sebab tu kami rapat,” jawab Husyairi tenang. Rambut belah tengahnya disebak ke
belakang apabila ditiup angin dari tepi. Matanya merenung Hanim yang duduk di
hadapannya sementara Hanim duduk menghadap laut. Hanya sesekali matanya
menjeling pemuda yang sentiasa tenang itu.
“Oh, macam tu. So, kau duduk dengan siapa sekarang? Er…
maksud aku, tinggal dengan family atau menyewa?” tanya Hanim lagi.
“Tinggal dengan family. Ibu saya tak benarkan saya menyewa
sebab rumah kami dah cukup besar untuk keluarga kami. Lagipun, takde sebab saya
nak menyewa sedangkan rumah dan kolej tak sampai lima belas minit perjalanan.”
Hanim mengangguk faham. Buat seketika, keadaan sunyi sekali lagi. Husyairi juga
sudah berpusing menghadap ke laut.
“Err… Hanim, awak memang dari kecil ke macam ni? Err…
maksud saya, comel macam ni?” soal Husyairi pula. Hanim tersengih dan mengangguk.
“Memang dari sekolah rendah aku dah tergolong dari golongan
gemuk…”
“Oh, begitu. Kalau macam tu, mesti kegemukan awak bukan
dari faktor pemakanan tapi dari keturunan. Betul tak tekaan saya?” Mendengar
sahaja perkataan keturunan, Hanim menggaru-garu dahinya yang tidak gatal
diiringi satu senyum tipis.
“Entahlah. Aku pun tak pasti!” balas Hanim selamba.
Husyairi mengerut dahi kerana pelik.
“Entah? Tak pasti? Apa maksud awak?” soal Husyairi lagi.
Hanim mengeluh. Laut yang beralun di hadapannya diperhati dengan hati yang
tenang walaupun keadaan alam yang malap mengganggu pemandangannya.
“Aku dibesarkan di rumah anak yatim,” jawab Hanim perlahan.
Husyairi tersentak. Tidak disangka Hanim yang suka bergurau dan ramah dengan
senyuman hidup sebatang kara begitu.
“Jadi, Hanim anak yatim lah? Maaf, kalau saya menyinggung
perasaan Hanim. Saya tak pernah tahu hal ni,” ucap Husyairi serba salah.
“It’s okey. Benda dah jadi, kita sebagai manusia tak boleh
melawan takdir. Cuma aku tak pasti samada aku ni anak yatim atau tak sebab
status aku lebih pada anak pungut. Orang jumpa aku kat tepi longkang lepas tu
aku dibawa ke rumah anak yatim. Tak pastilah cerita tu betul atau tak sebab aku
baru usia seminggu masa tu.”
“Takkan takde petunjuk langsung untuk cari parents awak?”
soal Husyairi lagi. Rasa ingin tahunya membuak-buak.
“Setahu aku takde. Umi yang jaga kitorang kat rumah anak
yatim tu cakap, aku hanya dijumpai hanya berbalut kain batik. Tarikh lahir aku
pun hospital yang tentukan,” ujar Hanim perlahan dan tenang.
“Mhm… siapa lagi yang tahu pasal ni?”
“Housemate aku semua tahu. Aku tak suka selindung benda
yang benar. Cuma Iqbal je yang tak tahu. Takde sebab untuk aku sebarkan perkara
ni. Aku cerita kat kau pun sebab kau tanya,” kata Hanim lagi. Riaknya langsung
tidak menunjukkan keresahan hanya ketenangan mengelilingi gadis berkulit hitam
manis itu.
“Awak tak pernah terfikir nak cari keluarga kandung awak?”
“Hus, aku dibuang tanpa sebarang tanda. Itu dah cukup untuk
memberitahu aku yang keluarga aku tak terima aku. Jadi, buat apa kita nak kejar
bayang-bayang yang kita sendiri tak nampak? Buang masa je. Lagipun, aku yakin.
Kalau Tuhan nak temukan aku dengan keluarga aku, Dia sendiri akan lakukan.”
“Tapi kalau tak usaha pun susah jugak,” ujar Husyairi lagi.
Hanim tersengih dan menggeleng.
“Lebih baik aku berusaha untuk menjadi pelukis komik yang
berjaya daripada berusaha sesuatu yang aku tak tahu. Dahlah, dah banyak sangat
aku cerita hal aku kat kau. Apakata, sekarang kau cerita kat aku pasal kau dan
Maria. Manalah tahu kalau-kalau aku boleh tolong? Kau ingat aku tak tahu kau
ada masalah dengan dia?” serkap Hanim.
“Maria? Mhm…” keluh Husyairi perlahan. Mukanya berubah
masam. Hanim mengerut dahi.
“Hus, kenapa? Salah ke aku tanya? Kalau kau rasa tak boleh
jawab, tak payahlah jawab…” ujar Hanim selamba. Husyairi menggeleng perlahan.
“Tak, awak tak salah cuma saya taknak bebankan orang lain
dalam masalah saya. Memang hubungan saya dengan Maria ada masalah dan tak pasti
masih ada atau tak jalan penyelesaiannya.” Husyairi tunduk setelah meraut muka.
Dia kelihatan begitu tertekan. Hanim menggeleng perlahan. Tubuhnya dipusing
betul-betul menghadap Husyairi.
“Hus, dalam dunia ni, takde masalah yang tak boleh
diselesaikan. Sekurang-kurangnya mesti ada satu jalan untuk menyelesaikannya,”
ujar Hanim lagi.
“Saya tak nafikan perkara tu, Hanim. Baiklah, saya akan
cerita kat awak.” Husyairi berpusing menghadap Hanim. Hanim menopang dagu dan
bersedia untuk mendengar masalah pemuda di hadapannya itu.
“Saya tak tahu dari mana nak mula. Mhm…sebenarnya, hubungan
kami ditentukan oleh keluarga. Kalau awak nak tahu, Maria tu seorang yang kuat
cemburu dan terlalu manja. Bagi dia, apa yang dia nak, dia akan sedaya upaya
untuk mendapatkannya dan begitu juga dengan saya. Saya tak nafikan, dia seorang
yang cantik dan sesiapa yang terpandang dia akan meminatinya. Dan kerana
kecantikan itulah yang membuat saya terperangkap. Kami bercinta dan saya
mengaku manja dan cemburu itulah yang membahagiakan saya. Tapi lama-kelamaan,
cemburu dia menjadi-jadi. Sampaikan member study group saya pun pernah diberi
amaran agar tidak rapat dengan saya. Saya rimas dengan cemburu buta dia. Saya
tahu mungkin sekarang ada seseorang sedang memerhatikan kita sebab terlalu
cemburu, dia sanggup mengupah pengintip untuk mengintip setiap kerja dan ke
mana saya pergi!” cerita Husyairi sayu. Hanim tersentak lantas menegakkan
tubuhnya. Matanya meliar memandang sekeliling. Tiada sesiapa melainkan mereka
berempat di kawasan itu.
“Err… rumit juga masalah kau ni. Aku ingat dalam tv je ada
perkara macam ni. Rupa-rupanya kat luar pun ada? Emm… aku harap, kau sabar je
lah Hus. Aku yakin, dia cemburu sebab terlalu sayangkan kau.” Husyairi
tiba-tiba tersenyum sinis dan menggelengkan kepala.
“Sayang? Betul ke dia sayangkan saya? Kalau dia betul-betul
sayangkan saya, dia takkan keluar dengan lelaki lain belakang saya. Ini amat
tak adil bagi saya. Saya tak boleh bercakap dengan perempuan, sedangkan dia
seronok keluar dengan lelaki lain. Sayang ke tu?” soal Husyairi kesal. Hanim
mengerut dahi. Kepalanya yang tidak gatal digaru sekejap.
“Sabarlah, Hus. Hanya itu yang aku boleh cakap. Aku bukan
taknak tolong kau tapi ini soal hati dan perasaan. Aku sendiri tak pernah buat
pakwe aku macam tu dan juga tak pernah diperlakukan sebegitu. Sabar, okey?”
kata Hanim lembut dengan senyum tipis.
“Awak ada pakwe?” soal Husyairi pelik. Hanim tidak pernah
menyebut tentang kekasihnya sebelum ini. Hanim tersengih.
“Kenapa? Tak percaya?” Hanim ketawa kecil dan Husyairi
semakin pelik.
“Ya, dulu aku ada pakwe tapi terputus di tengah jalan sebab
masa tu aku sekolah lagi. Kami putus pun suka sama suka sebab nak tumpu pada
pelajaran. Tapi kau nak tahu, aku masih sayangkan dia sampai sekarang cuma aku
tak tahu dia ada kat mana dan sedang buat apa sekarang. Aku juga yakin, kalau
jodoh kami kuat, Tuhan pasti temukan kami kembali.” Hanim tersenyum manis.
Wajah Mahadi bermain-main di matanya. Husyairi tersenyum kecil.
“Dari wajah awak, saya dah boleh nampak sayang awak pada
dia. Err… badan dia macam awak ke?” tanya Husyairi berhati-hati agar tidak
menyinggung hati kecil gadis itu.
“Badan dia, tinggi dia, warna kulit semuanya macam kau.
Sebab tu, masa pertama kali kita jumpa dulu, aku asyik tersenyum sebab
teringatkan dia. Tapi dia taklah sekacak kau. Dia tak tampan tapi dia manis.
Kalau dia senyum, makin manis aku tengok dia,” cerita Hanim masih dengan
senyuman khayalnya.
“Biasalah tu. Kalau hati dah cinta, seburuk mana pun
fizikal seseorang tu, dia tetap nampak cantik. Dan saya percaya, kecantikan tu
datangnya dari dalam. Macam sekarang, saya tak pernah fikir awak ni badan besar
ataupun tak cantik sebab setiap kali kita jumpa, awak tak pernah tunjuk
kelemahan yang ada pada awak. Pada pendapat saya, awak ni jenis periang dan
saya takkan mampu fikir awak seorang yang bermasalah dengan sikap awak sekarang
ni.” Hanim tersengih mendengar pendapat Husyairi itu.
“Dahlah, jangan terlalu memuji takut nanti kau salah
tafsir. Hus,kalau kau nak tahu, aku sendiri tak pasti apa karakter yang ada
pada aku. Yang aku tahu, aku sekarang memang gembira dengan kawan-kawan dan
sesiapa saja yang rapat dengan aku. Tapi, aku ni manusia biasa. Kadang-kadang
tu ada masalah jugak cuma aku selesaikan sendiri.” Husyairi tersenyum mendengar
kata-kata yang penuh dengan keyakinan itu.
“Eh, sedar tak sedar dah pukul 11.00 rupanya? Diorang ni
tak tahu nak balik ke?” soal Hanim sambil mencari pasangan Laila dan Iqbal.
Matanya tertancap pada dua susuk tubuh yang sedang duduk di bawah pokok kelapa.
Hanim menggelengkan kepala.
“Kau tengoklah tu, Hus. Siang tadi gaduh bagai nak rak. Bila
dah jumpa macam belangkas. Tak faham aku dengan diorang ni!” ujar Hanim dengan
dengus perlahan.
“Biarlah diorang nak buat apa pun. Janji jangan buat benda
tak elok dah lah. Kenapa? Awak dah ngantuk ke?” tanya Husyairi tenang.
“Bukan mengantuk, cuma letih sikit. Tadi aku ada
pembentangan projek lukisan. Sibuk sangat sampai nak rehat pun takde masa.
Balik tengahari pulak, jumpa dengan si Iqbal tu. Sampai rumah dah nak dekat
maghrib. Lepas Isyak, Ila ajak keluar makan. Tu yang letih tu!” keluh Hanim
sambil bercerita jadualnya yang padat hari itu.
“Aik, jumpa Iqbal dari tengahari sampai maghrib? Lamanya?”
soal Husyairi pelik.
“Kitorang bukan jumpa dekat sini. Dia suruh aku turun
Seremban. Nak taknak, sebab nak tolong kawan punya pasal, aku turunlah jugak!”
jelas Hanim selamba.
“Oh, patutlah Iqbal muncul depan rumah saya petang tadi.
Rupa-rupanya baru lepas dating dengan awak?” usik Husyairi dengan senyum nakal.
“Tolong sikit! Jumpa tu meeting bukan dating!” tegas Hanim.
Husyairi ketawa kecil.
“Kalau awak nak balik dulu, saya boleh hantarkan. Lagipun
kita kan naik motor masing-masing.” Husyairi kembali tenang setelah tawanya
reda. Hanim senyap sambil berfikir. Akhirnya, dia mengangguk dengan senyuman.
Mereka berdua beredar menuju ke arah Laila dan Iqbal.
“Iqbal, kitorang balik dululah. Hanim kata dia letih,”
beritahu Husyairi. Hanim di sisinya mengangguk.
“Yelah, Laila. Aku dah letih sangat ni. Korang jangan balik
lewat sangat. Bahaya!” pesan Hanim. Setelah mendapat persetujuan pasangan itu,
mereka berdua kembali ke motor Husyairi.
Husyairi memakai helmetnya begitu juga dengan Hanim.
Walaubagaimanapun, Husyairi terpaksa memasang tali helmet Hanim kerana Hanim
tidak tahu bagaimana untuk mengancingnya. Ketika itu juga ada satu cahaya silau
menyinari mata mereka buat seketika. Hanim dan Husyairi tersentak. Mereka
memandang sekeliling. Sunyi.
“Apa benda tadi tu hah?” soal Hanim pelik. Husyairi
mengangkat bahu dengan wajah selamba lalu menghidupkan enjin motornya. Hanim
membonceng belakang motor itu.
Sepuluh minit kemudian, mereka tiba di perhentian bas yang
terletak di hadapan apartment Pantai Indah di mana tempat Hanim dan
rakan-rakannya menyewa. Hanim turun lalu mengurut lututnya yang agak
menggeletar dengan kelajuan Husyairi mengawal motornya di jalanan. Husyairi tersenyum
dan menggeleng. Hanim memegang tiang perhentian bas itu lalu duduk di bangku
batu di situ. Husyairi mematikan enjin motornya lalu segera mendapatkan Hanim.
“Awak takde apa-apa? Maaflah, tadi saya sengaja bawak laju.
Saya rasa pegangan awak kat bahu saya makin lama makin longgar. Awak ngantuk
ke?” soal Husyairi beriak bimbang. Rasa serba salah menguasai hatinya. Hanim
mengeluh.
“Ha’ah, mengantuk sikit. Aku tak pernah rasa mengantuk
macam ni. Mungkin penat sangat,” jelas Hanim perlahan. Husyairi mengangguk
faham. Dia membantu membuka helmet di kepala Hanim.
“Awak betul ke okey ni? Kalau tak, saya hantarkan awak
sampai atas,” tawar Husyairi ikhlas. Hanim pantas menggeleng.
“Eh, takpe-takpe! Aku boleh jalan sendiri. Kau nak balik
dulu, baliklah. Ala, kalau aku tak boleh jalan pun, pakcik guard tu ada. Dia
boleh tolong hantar aku sampai atas.”
“Hanim, awak ingat saya ni kejam sangat ke nak biarkan awak
macam ni? Saya akan teman awak kat sini sampai awak boleh naik sendiri.” Hanim
tersentak. Namun, Husyairi hanya berwajah selamba sambil membuka helmet di
kepalanya pula. Hanim mengeluh perlahan. Matanya sudah letih untuk berjaga
seperti selalu. Dia cuba berdiri tapi kakinya masih terasa kebas dan lemah
untuk melangkah. Hanim menepuk kakinya dengan perasaan geram. Husyairi hanya
menggelengkan kepala.
“Dahlah, mari saya hantar awak ke atas. Tak payahlah nak
degil sangat…” ujar Husyairi lantas memapah Hanim masuk ke kawasan apartment.
Setibanya mereka di pintu apartment, Husyairi pantas mengetuk pintu sebelum Hanim
bersuara. Tidak sampai seminit, seorang gadis berambut lurus potongan bulat
membuka pintu.
“Hoi, Hanim! Kenapa dengan kau ni?” soal Irni terkejut.
Belum sempat Hanim bersuara, Husyairi menjelaskannya.
“Sebenarnya, kaki dia lemah sebab saya bawa motor laju
sangat. Tak sangka pulak boleh jadi macam ni.” Irni lantas ketawa. Hanim
memasamkan muka dengan jelingan tajam.
“Dahlah, masuklah papah dia! Kami tak mampu nak papah dia
ni!” ujar Irni selamba dengan tawa yang bersisa. Husyairi hanya mengukir senyum
tipis lalu membantu Hanim membuka sandal gadis gempal itu. Hanim tiba-tiba
berasa segan apabila Husyairi membuka sandalnya. Tangan kirinya memaut pintu,
manakala tangan kanannya masih di bahu Husyairi. Hanim mengutuk diri sendiri
dalam hati di atas perkara itu. Husyairi memapah Hanim masuk ke apartment
bujang itu. Hanim duduk di sofa di ruang tamu.
“Terima kasih, Hus. Aku ni menyusahkan kau je!” ucap Hanim
perlahan. Husyairi yang berdiri di sisinya hanya mengukir senyum. Zulaikha dan
Irni tersengih. Irni merenung Husyairi penuh minat.
“Takde apa yang menyusahkan. Kalau awak nak saya papah
sampai bilik awak pun saya tak kisah. Bukan susah sangat pun!” balas Husyairi
dengan senyum manis. Hanim tersentak.
“Hish, selisih malaikat 44!” ujar Hanim pantas. Husyairi dan
Zulaikha ketawa melihat Hanim yang menggelabah. Hanya Irni yang masih tekun
meneliti setiap inci wajah Husyairi.
“Okeylah, Hanim. Saya balik dulu. Kalau ada apa-apa, call
lah saya. Saya rasa, as a friend tak kisah kalau kita keluar lagi. Kalau ada
masalah jangan segan-segan minta tolong saya.” Husyairi mengeluarkan dompetnya
lalu menghulur sekeping kad nama kepada Hanim. Hanim mengangkat kening pelik.
Kad itu tetap disambut meskipun di kepalanya sarat dengan persoalan tentang
kebaikan dan keramahan jejaka pendiam itu. Setelah Husyairi hilang di sebalik
pintu, Zulaikha segera menutup pintu manakala Irni segera mendapatkan Hanim.
Hanim sedang merenung kad yang tertulis nama MUHAMMAD FAROUK HUSYAIRI BIN ABDULLAH
itu.
“Handsomenya kawan kau tu, Hanim! Cara dia cakap pun
lembut. Kalau lah aku dapat pakwe macam tu…” Irni mula memasang angan. Hanim
mengerut dahi.
“Kau nak ke? Nah, ambiklah!” ujar Hanim sambil menghulur
kad nama tadi.
“Betul ke ni? Kau tak menyesal?” duga Irni gembira. Hanim
tersengih. Zulaikha merenung Irni dengan hati yang kurang senang.
“Irni, itukan kawan Hanim. Kau jangan nak potong line
pulak!” tegur Zulaikha tegas.
“Dah Hanim yang nak bagi aku kenal dengan mamat tu, apa
salahnya? Lagipun, diorang kawan bukan pakwe makwe kan?” balas Irni selamba.
“Dah…dah! Nah, ambiklah kad ni. Kalau aku nak call dia,
Iqbal boleh bagi aku nombor dia. Ika, biarlah Irni nak kenal dengan Husyairi.
Irni kan masih single?” ujar Hanim selamba. Irni mencapai kad itu lalu dicium
berkali-kali. Zulaikha mendengus perlahan.
“Kau pun masih single kan?” soal Zulaikha tegas.
“Aku lain. Takde maknanya si Hus tu nak pandang aku. He
just my friend. Aku jumpa dia pun baru tiga kali. Manalah tahu, kalau-kalau dia
ada jodoh pulak dengan Irni ni…” usik Hanim. Irni tersenyum malu. Zulaikha
mencebik.

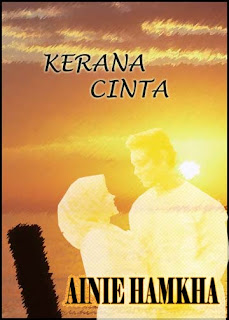
Tiada ulasan:
Catat Ulasan